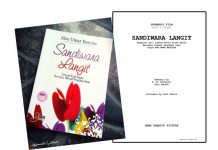Diary Tyas
Sudah hari ke-26 aku menikmati tiap sisi ruang putih ini.
Suhu udara pendingin berada di angka 16 derajat celcius.
Sore ini, aku merinduimu serupa rintik hujan.
Cerita lalu begitu menggerimis serupa dongeng.
Tentang ribuan capung yang terbang mengitari kembang-kembang layu.
Juga tentang kupu-kupu yang lemah pada matahari.
Nanar kutatap langit melalui bening kaca jendela ruangan ini.
Adakalanya abu-abu.
Namun sesekali membiru.
Ada luka yang tersembunyi dalam dekapan bantal yang kusentuh.
Ini hanya keluh dan peluh.
Berharap kelak engkau hadir membasuh.
Meski rasamu tak lagi utuh.
Pernah suatu hari, aku berhayal, Tuhan akan memberiku waktu untuk temukan dirimu. Lalu berdua kita menikmati dingin hujan, serta tanah basah.
Gigil dingin tak lagi terasa.
Berhayal tentang asamu yang tak pernah lelah. Mengejar ribuan rintik, lalu tanganmu mengelus pipiku sesaat. Sebelum pelangi hadir hiasi langit dengan kilauan warnanya.
Tak bisa melupakanmu. Bayangmu selalu hadir dalam rasaku.
Semua masih terangkum manis. Semanis cinta dan janji yang pernah terucap, “Sayang, saatnya nanti. aku kan datang bersama hujan, tuk menghapus tangismu pada malam ketika derai airmata tak mampu lagi kau tampung di mata kecilmu.”
Tanpa terasa kesedihan pun perlahan menggunung, dan hanya mampu mengingat janji yang sempat kau ingkari.
Ini senja ke-26 saat kau mengirim pesan singkat. Aku masih harus berada di ruang putih ini menikmati kebaikan dan kasih sayang-Nya.
Tuhan itu Maha baik, aku masih harus menunggu leukositku turun dari angka 22.000 mm3 meski hb sudah semakin membaik. Yang wajib kau tau adalah… bahagiaku. Ya, bahagia karena sudah lima tahun aku diberi remisi oleh Tuhan untuk menikmati apa-apa yang ditetapkan-Nya.
Masih berharap kelak Tuhan mempertemukan aku, kamu dan hujan tuk luruhkan janji yang siap ku tunaikan.
Waktu terus merambat.
Jarum jam terus berdetik.
Masih ditemani notebook, aku mencoba mengeja huruf, merangkai kata yang serupa puzzle kehidupan.
Hawa dingin malam mulai menyapa. Udaranya menusuk, menembus cardigan yang membalut tubuh kurusku.
Satu demi satu huruf mulai kueja dengan segenap hati dan pikiran. Mendadak lamunanku kabur ketika ayah tercinta masuk ke ruangan dan menyapa. “Sudah mulai malam Alya. Belum tidur juga?” sapa ayah.
“Alya gak bisa tidur Yah, entah kenapa, padahal semua uneg-uneg sudah Alya tumpahkan kepada-Nya.”
“Apa yang menjadi pikiranmu Alya? Atau kamu masih memikirkan Bayu?” tanya ayah mencoba mencari tau.
“Memikirkan mas Bayu rasanya sia-sia Yah… Dia sudah menjadi milik orang lain. Satu nama telah mengisi hatinya, dan dia juga telah menikah… Alya menikmati kesendirian ini kok Yah.”
“Tapi Bayu masih berkirim kabar kan?” ayah mencoba menyelidik lagi.
“Sudah gak pernah Yah, dan Alya memang sudah berjanji pada diri Alya untuk gak menghubungi atau berkirim kabar lagi sama mas Bayu. Alya gak ingin mengganggu kebahagiannya. Alya bukan pilihan Yah, karena Alya memang tak pantas dipilih laki-laki manapun…,” jawabku meyakinkan ayah.
Ayah tak menjawab, hanya matanya saja yang menyiratkan perih saat mendengar jawabanku. Perlahan ayah mendekatiku, anak gadisnya yang telah merangkak di usia 30 tahun. Jarum jam terus bergerak. Tanpa terasa sudah lewat tengah malam.
Sementara aku dan ayah masih terus berdiskusi dan saling menguatkan. Aku dan ayah saling bersitatap, berusaha menerjemahkan apa yang sama-sama tak terucap. Namun akhirnya ayah dengan berat hati mencoba menguatkan dan meyakinkanku.
“Saat ini Alya memang bukan pilihan nak…, tapi ayah yakin suatu saat Allah akan hadirkan laki-laki terbaik menurut-Nya yang akan memilihmu,” ucap ayah lirih sembari mengusap rambutku yang nyaris habis.
“Ayah tau betapa sulitnya dirimu menerima semua ini. Membayangkan andaikan ayah ada di posisimu pastilah ayah sudah putus asa. Bertahanlah untuk ayah…, karena Alya adalah semangat hidup ayah, setelah meninggalnya ibumu sepuluh tahun lalu,” gumam ayah kelu melihat keterpurukanku.
Sementara bibirku masih terkatup. Tak ada sepatah kata pun yang mampu kuucapkan. Lalu perlahan ayah meraih tanganku sembari berucap, “Masih ingat anak-anak bangsal empat kan Alya?” Aku mengangguk. “Mereka semua merindukan hadirmu. Mereka sahabat kecilmu. Mereka mengais asa mengalahkan rasa sakit itu, dan mereka sama sepertimu anakku. Kita sama-sama ikhtiar. Ayah tau itu tidak mudah tetapi selama nafas masih melekat, kewajiban kita adalah berusaha dan itu wajib. Yakinlah bahwa Allah tak akan menguji hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Ingatlah Alya, bahwa Alya tidak sendiri, Allah senantiasa ada di setiap tarikan nafasmu, ada ayah, juga sahabat-sahabatmu yang merindukan hadirmu.”
Aku masih tetap membisu. Derai airmataku mulai menggunung, dan tak mampu dibendung lagi, yang perlahan pecah serta membuncah. Kebesaran jiwa ayah yang tak pernah surut untuk menyemangati hidupku adalah beban yang kadang kurasakan, di tengah keterpurukan ini.
Kadang hadir perasaan bahwa diri ini tak berguna bagi siapapun. Hatiku bergemuruh serupa ombak yang berdeburan di lautan lepas. Tak tau harus bagaimana. Haruskah aku menyalahkan Tuhan? Haruskah aku bertanya kenapa aku harus dilahirkan? Atau aku menyalahkan ibuku yang sudah tenang di haribaan-Nya?
Waktu masih terus bergulir. Perbincangan antara ayah dan aku mengalir serupa butir-butir air yang menitik pada daun-daun dan rumput ilalang. Lalu kupandang wajah ayah dalam-dalam. Kami berdua masih bersitatap. Masing-masing bicara dengan hati serupa isyarat bahwa kita saling memahami.
Perlahan tubuhku telah rebah dalam pelukan ayah. Hangat kurasakan pelukan kasih sayang ayah yang tak ingin kehilangan anak tercintanya. Tangisanku pun pecah di antara adzan subuh yang bergemuruh.
Dalam ke-tertatihan, aku melangkahkan kaki mencoba menata diri, juga hati. Aku mencoba berdialog dengan hati. Sadar bahwa airmata tak jua menyelesaikan apa pun yang kurasakan. Satu demi satu kubasuh wajah ini dengan bulir bulir air wudhu. Lalu kuraih sajadah sebagai alas untuk berkeluh juga berpeluh.
Pagi ini kutumpahkan segala beban rasa yang ada dalam pikiran ini. Tak ada satupun yang tertinggal. Lalu menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Hidup dan Pemilik Waktu. Rasa syukur pun hadir… Aku sadar bahwa diri ini masih memiliki Tuhan yang menguatkanku, punya keluarga, dan sahabat-sahabat yang begitu menyayangiku.
Leukemia bukan akhir dari segalanya. Karena raga boleh saja sakit, tetapi jalan hidup yang telah ditetapkan-Nya harus tetap kulalui selama nafas masih melekat dalam diri. Dan Tuhan senantiasa ada dalam kebagahiaan, maupun dalam keterpurukan. Begitupun keluarga juga sahabat kita. Aku mencoba mengurai senyum.