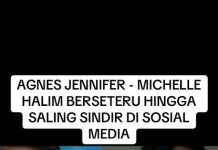Penulis: Sunardian Wirodono
Di sebuah warung kopi. Malam hari. Sepi. Tak ada pengawalan khusus. Cakrabirawa? Lagi rokokan sambil nonton sinetron. Mbah Wongso seperti biasa, terkantuk-kantuk di depan anglo yang menyala abadi.
Di hadapanku, Bung Karno duduk tenang. Pencipta mimpi-mimpi besar. Tiba-tiba ia mengagetkanku, “Heh, anak muda gondrong! Apa kabar Indonesia di tahun 2025?”
Tak segera kujawab. Agak sedikit berdrama, aku teguk kopi itemku. Pahit, seperti sejarah negriku.
“Negara jalan mundur, Bung.”
“Mundur?” Bung Karno hampir tersedak gelas kopinya. “Kenapa bisa? Reformasi itu kan semangat kemajuan!”
“Reformasi kayak pita kaset, Bung. Udah bolak-balik diputer, suaranya sember. Setelah reformasi, kita punya demokrasi. Tapi makin ke sini, demokrasi jadi kayak warisan. Dilelang. Orde Baru bangkit, bukan dari kuburan, tapi dari Google Meet dan aplikasi pertemanan politik. Sebentar lagi langkah mundur akan sampai ke Orde Lama. Bukan karena semangat revolusi belum selesai, tapi dari nostalgia salah alamat,” aku berapi-api.
“Orde Lama kan lebih baik dari Orde Baru?” sergah si Bung.
“Kata siapa?” aku tak mau kalah sergah, “Orde Lama juga ada korupsi, Cuma pembicaraan yang ideologis masih ada sih, nggak sepragmatis Soeharto.”
“Lalu siapa yang salah?” lagi-lagi Bung Karno kegusaran.
“Pemimpinnya,” tukasku. “Dan rakyatnya. Pemimpinnya korup dan oportunis. Rakyatnya cuek dan narsis. Kita ini bukan cuma kena serangan siber, tapi serangan sindir dan sindrom ‘asal bukan gue’.”
“Kapitalisme, sosialisme, komunisme —apa masih relevan?” wajah Bung Karno serius, namun suaranya makin lirih. Takut Tim Mawar masih gentayangan.
“Kapitalisme itu oke, Bung, asal nggak korup, juga jika mau berbagi” kataku seolah ngajarin Bung Karno. “Bisa jadi kendaraan bersama sesungguhnya. Tapi kita ini lucu: Kapitalistik pas mau ngeruk sumber daya. Sosialis pas kampanye. Monopoli pas bisnis keluarga mulai ekspansi.”
“Contoh?”
“Janji lindungi petani, tapi petaninya disuruh ikut pelatihan digital, bukan dikasih pupuk. Janji harga stabil, tapi stabilitas diukur pakai algoritma penuh misteri. Janji merdeka belajar, tapi merdeka korupsi pula. Bahkan, Bung… sekarang lebih gampang nyari ijazah palsu daripada nyari air bersih di kota industri.”
“Jadi Prabowo mau membawa Indonesia ke mana?” tanya Bung Karno, skeptis.
“Prabowo kayaknya juga bingung, Bung. Kadang dia mau jadi Macan Revolusi. Kadang mau jadi CEO perusahaan negara. Kadang mau jadi Petani Digital. Tapi yang jelas, senyampang dia lebih mirip seperti mau nyusun ulang peran bapaknya —Sumitro Djojohadikusumo. Cuma tanpa kerangka ideologi yang solid.”
Negara sudah tersambung ke semua arah. Satu tangan ke kapitalisme, tangan satunya sosialisme, tapi kakinya kepleset di got oligarki
“Astaga…” Bung Karno terbelalak, “Jadi apa yang bisa aku lakukan?”
Aku tatap wajah Bung Karno. Ia terlihat letih, seperti sedang menonton sinetron dengan naskah yang basi, tapi aktornya terlalu serius.
“Bung, saya punya ide,” tak tahan aku ngomong ke Bung Karno. “Mending Bung main sinetron aja. Jadi superhero. Judulnya: ‘Satria Pembela Transkrip Bangsa!’ Tugas Bung: membongkar semua yang palsu-palsu, dari sejarah hingga ijazah palsu. Jadi pemutar waktu ke masa lalu.”
“Wah, itu ide gila! Tapi aku suka,” Bung Karno terlihat antusias.
Dan malam semakin sunyi –lalu, kumainkan gitar, Leo Kristi nyeletuk. Aku kini tahu satu hal: Indonesia bukan kekurangan tokoh besar. Kita hanya kehabisan penonton yang tahu membedakan mana drama, mana sejarah.
Makjegagig, kami berdua kaget, barusan masuk Sri Mulyani dan Tan Malaka. Sepertinya, keduanya lagi “mabok”.
Mbah Wongso sebentar melek, kemudian merem lagi. Tungku di depannya menyala abadi***
–